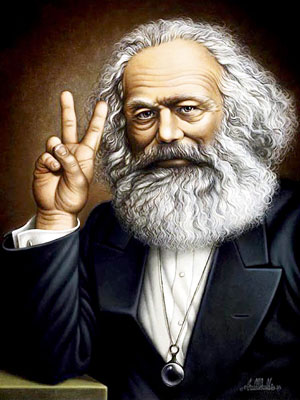Bagi seorang santri
yang mempelajari pemikiran Karl Marx, jelas akan menemukan kesulitan-kesulitan yang
pelik, rumit bahkan membosankan. Kesulitan pertama, terdapat dalam instrumen
referensi yang tentu saja tidak disediakan dengan manja oleh pesantren, tidak
seperti kitab-kitab ulama’ muslim Abad Pertengahan yang tersedia langsung di perpustakaan.
Kedua, Marxis dalam dunia pesantren kurang populer sebagai sebuah diskursus
intelektual di kalangan santri. Sehingga bagi peminat Marxis, ia akan menemukan
kesulitan untuk berinteraksi wacana dalam melakukan kritik dan otokritik
tentang seluk-beluk pengembangan ilmu pengetahuannya tentang Marxis itu.
Dan kesulitan yang
ketiga, Marxisme dalam spektrum pemikiran Islam dan/atau pesantren, masih dianggap
sebagai tendensi berpikir yang cenderung liberal bahkan “anti tuhan”. Sehingga,
bagi pengagum Marx dalam dunia pesantren, ia akan selalu dicurigai sebagai
santri yang tidak taat beragama. Kesuliatan yang terakhir ini, sebenarnya bukan
hanya terjadi di kalangan pesantren, tapi juga terjadi pada banyak orang yang
kadang hanya secuil mempelajari khazanah pemikiran Marx, dan parahnya langsung
menyimpulkan bahwa Marx adalah ateis, komunis, dst.
Dari itulah,
bergelut dalam pemikiran Marxis di dunia pesantren adalah pertaruhan.
Pertaruhan apakah nanti ia akan benar-benar intens dalam studinya itu, atau
menyerah pada realitas yang seolah-olah tak dapat menghendaki sebuah pemikiran
Marxis tumbuh subur melampai tradisi keilmuan yang sudah sejak dulu
dikembangkan sebagai kurikulum pesantren itu sendiri. Tapi bagi saya, santri
(saat ini) harus menjadi Marxis. Hal ini bertolak dari kosmologi kaum santri
yang kini sudah nyaris sirna elastisitasnya dan paradigma kritisnya.
***
Mengapa santri
harus menjadi Marxis? Tentu bukan untuk membangun serikat buruh dan bermaksud
melenyapkan tradisi keilmuan pesantren, yang oleh Wali Songo dan para kiai-kiai
sepuh sudah dipraktikkan sejak Islam menginjakkan petamakali di bumi Nusantara ini.
Alasan vital santri harus menjadi Marxis, adalah berdasarkan situasi santri itu sendiri. Satu konstelasi ekonomi-politik yang
meletakkan posisi santri sebagai kelas proletar yang terpinggirkan.
Bertahan dalam tradisionalitas, hanya akan membuat
santri diam dalam penderitaan yang tak ia sadari. Pradigma tradisional
pesantren terlalu “purba” untuk merangkai gerakan
yang secara agresif, kuat dan revolusioner. Sebagai
strategi sosial, “tradisionalisme pesantren” terlalu lugu untuk bersaing dengan
wacana atau bahkan praktik-praktik kapitalisme global. Pada fase inilah,
Marxisme menjadi kebutuhan untuk merekonstruksi strategi gerakan para santri—atau dalam hal ini Islam—di tengah
struktur masyarakat yang modern-kapital.
Maka dari itu, bagi
santri yang belajar Marxisme, berati ia juga harus mengupayakan—yang tentu tak
sederhana—mempertemukan gagasan religius keagamaan—atau lebih spesifik keIslaman—denagan
prangkat metodologi Marxisme. Eksperimentasi intelektual ini, di Indonesia sudah
pernah dilakukan oleh beberapa orang yang lahir dari kultur pesantren, termasuk
dulu yang pernah dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid. Gus Dur pernah menulis artikel
pendek tentang, “Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme”, tahun 1982. Dewasa
ini, dilajutkan oleh Muhammad Al-Fayyadl,
penulis yang juga cukup intens melakukan pembacaan ulang khazanah keIslaman
kita melalui kerangka Marxisme. Tapi kedua orang tersebut tidak sampai pada
wilayah spesifik pesantren, sebagai satu wacana strategis tentang Islam Indonesia.
Jadi, rumusan
tentang “Santri-Marxisme”, yang saya lakukan saat ini, tidak bisa disebut usaha
yang baru. Kecuali pada domain penekanannya yang lebih khusus dalam aspek
kritik dan pembacaan ulang agama dan identitaas kesantrian dihadapkan dengan
ideologi ekopol yang hari ini memporak-porandakan tatanan sosial kaum
tradisional yang sejak dulu menjadi basis sosio-kultural pesantren dan santri. Sebagai
eksperimentasi metodologis, Santri-Marxisme merupakan kristalisasi dari jejak pemikir-pemikir
Islam kontemporer dewasa ini. Kita bisa menyebut misalkan, Ali Syari’ati, Mohammd
Arkoun, Hasan Hanafi dan Asghar Ali Engenair, sebagai pemikir yang telah
berhasil melampaui garis normatif ajaran Islam itu sendiri, dalam proyek
rekonstruksi ajaran kritis Islam dan untuk kebaikan Islam itu sendiri.
Oleh karena itu,
santri yang belajar Marxis di pesantren adalah bentuk ijtihad menghadapi
realitasnya sendiri. Karena tanpa model ijtihad semacam ini, santri tidak akan
menemukan persoalan-persoalan: “eksploitasi ekonomi”, “kapitalisme”,
“kontradiksi sosial”, “struktur” dan istilah-istilah seperti:
“borjuis-proletar” dalam dunia kitab kuning yang menjadi kawan akrabnya
sejak dulu. Sementara di dunia luar, di mana ia akan menginjakkan kaki dan
hidup berkhidmat di tempat itu, persoalan-persoalan dalam studi Marxisme seperti
di atas, riil terjadi. Inilah kemudian, “Santri-Marxisme” menduduki tempatnya
yang paling vital dihadapkan dunia di mana nanti para santri itu sendiri hidup.
Karena bagaimana pun,
santri sampai hari ini, masih diterjemahkan sebagai identitas keIslaman
nusantara. Dalam kosmologi santri, juga melekat khas Islam masyarakat akar
rumput, Islam pinggiran, Islam petani, yang keberadaannya kini dalam struktur
sosial nasional maupun global, termarjinalkan sebagai kelompok yang tak punya
akses politik, nyaris miskin permanen, dan jauh dari nasib sejahtera. Dalam
studi Marxisme, kita bisa menyebut santri ini sebagai kelompok sosial ploretarians.
Sebagai kaum
ploretar, tentu, ia memahami kondisinya beserta seluruh problem yang dihadapi
bertolak dari posisi matrialis. Bahwa problem sosial yang kini menimpa kaum
santri bukan sekedar persoalan moral dan apa pun itu menyangkut relasi dan
dimensi vetikal-spiritual. Melainkan persoalan yang lahir dalam khazah sosial
empirik yang erat kaitannya dangan desain politik-ekonomi para elit politik dan
pemilik modal, yang ingin mengaup keuntungan indevidual.
Berangkat dari
fenomena itulah, melalui lanskap Santri-Marxisme, saya ingin menyebut Islam santri,
sebagai “Islam ploretar”: Islam yang bersemi
dan hidup di wilayah pinggir, pedesaan dan mayoritas terdiri dari masyarakat
kelas bawah. Walaupun mereka bukan seutuhnya buruh—sebagaimana terminologi ploretarians ala Marxisme—namun,
mentalitasnya berhadapan dengan ideologi ekonomi dan politik nasional
lebih-lebih global, mereka tidak ada bedanya dengan budak; sebagai pekerja
rajin tanpa penghasilan setimpal dari institutsi, kantor atau pabrik di mana
mereka bekerja. Sebagai kelompok proletar, posisi santri, mau tidak mau, kini
harus di pahami sebagai subjek yang berada dalam posisi “alienasi”. Betapa tidak, dalam tatanan sosial, ia adalah komunitas
yang berada pada base structure, yang
“menghamba” pada kuasa kelas suprastructure
borjuis, yakni: para teknokrat, dan korporat. Semantara dari dulu, tak ada sejarah penghambaan santri pada siapapun,
kecuali penghambaannya
terhadap Allah SWT. Bahkan ia selalu
melawan atas segala bentuk tindak kolonialisme Belanda dan Jepang.
Di sinilah,
Santri-Marxisme hadir tidak sekedar berupa eksplorasi konseptual yang canggih
dan ujung-ujungnya, kandas dengan hasil yang kosong. Santri-Marxisme ingin secara kongkret mengembalikan posisi
santri sebagaimana yang dahulu; merebut kembali stabilitas yang selama ini
telah sirna. Dari itulah, Santri-Marxisme ingin membawa Islam pada wilayah yang
lebih praksis dan material, mengunakan
prangkat dogma untuk melakukan perjuangan kelas. Dalam dialektika kehidupannya,
tepat sebagaimana Marx, ia harus memahami: “the
history of hitherto all existing society is the history of class stuggles”
(sejarah seluruh kehidupan sosial sampai sekarang adalah sejarah perjuangan
kelas). Santri harus bangkit dari posisinya sebagai kelas ploretar.
***
Nah, saya ingin
lebih spesifik berbicara dalam konteks Madura. Di Madura, dari dulu hingga
kini, secara kultural adalah basis pesantren, banyak pesantren besar yang
hingga detik ini menampung beribu-ribu santri seperti di Annuqayah Guluk-Guluk
dan Al-Amin Parenduen. Sehingga tidak heran, mayoritas penduduk Madura adalah santri;
berbicara Islam di Madura, maka sama saja dengan berbicara santri di Madura. Santri
dalam dialektika Islam Madura, bukan sekedar simbol historis dari situasi masa
lalu, namun ia memang ekspresi Islam Madura hingga detik ini dan sampai
kapanpun nanti. Dari itulah, dalam Islam Madura: saat identitas santri telah
remuk dalam jaring laba-laba kapitalisme, maka itu pula berati Islam dalam
keadaan yang sama.
Islam di Madura sebagai
“Islam proletar”, di mana pemeluknya mayoritas terdiri dari para pekerja, kuli,
petani, setiap saat senantiasa tereksploitasi secara ekonimis oleh struktur
besar kekuasaan. Bahkan dalam praktik politik pun, mereka hanya boneka. Sebagaimana
boneka, mereka tak berdaya pada sang pemilik, dibuat untuk apa pun boneka itu,
adalah kuasa sang pemilik. Mereka dicipta sebagai sapi perahan untuk diperas agar
menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Kesadarannya secara dominan dirumuskan
secara hegemonik, inilah yang kemudian oleh Michel Foucault disebut sebagai,
“kematian manusia” (the death of human).
Masyarakat muslim Madura
yang kini dalam kubang kapitalisme, harus menyadari bahwa dirinya berada dalam
tirani yang secara nyata melanggar prisip-prinsip kemanusiaannya. Yang dalam
perkembangannya nanti, akan menghancurkan sendi-sendi idealisme kaum santri
sebagai representator Islam di Madura. Hingga akhirnya membuat Islam Madura
beku, bisu dan absen dari aksi-aksi perlawanan terhadap seluruh bentuk
eksploitasi yang sejatinya telah mencedrai hak primordial rakyat.
Baik, mari kita
tunjuk langsung. Selama ini, kalangan kelas menengah keatas, di Sumenep sedang
merepatkan barisan untuk menyulap dirinya sebagai kelas elit bourjuis. Gerakan
borjuis ini, terdiri dari para pengusaha yang memiliki basis politik sangat kuat
di meja pemerintahan. Kekuatan politiknya digunakan untuk mengaup keuntungan
pribadi untuk semakin tampil lebih dominan di tengah-tengah masyarakat.
Fatwa-fatwa tentang kemajuan dan pembangunan adalah kata-kata kunci yang sering
mereka ucapkan ke masyarakat desa, yang cenderung tak berpikir dua kali tentang
masa depannnya.
Gerakan ini semakin
berkembang, saat mereka juga mampu berafiliasi dengan kelas intelektual dan
seluruh media pers, cetak maupun online. Organisasi dan Komunitas
diskusi/literasi yang lahir dari gerakan borjuis ini di Sumenep sudah bertaburan.
Hal ini, digunakan oleh para elit politik dan pemodal itu untuk memperkuat status
quo-nya di hadapan publik. Kita bisa melihat banyak gerakan aktivis yang
tidak memiliki basis idelisme yang kokoh, juga ikut meremaikan serangkaian
gerakan berjuis ini.
Pada titik
klimaksnya, kini gerakan elit kelas menengah keatas—untuk tidak menyebut
sebagai kelas borjuis—tampil di hadapan publik, dengan dalih kemajuan dan
pembangunan, yaitu: gagasan Visit Sumenep. Visit Sumenep, ingin menyulap kota
santri yang religius ini, menjadi kota wisata. Proses pemebangunnya sudah mulai
dilakukan. Para elit ini, bekerja sama dengan sejumlah investor lokal dan luar
negeri dalam tahap pembelian tanah. Pembelian tanah, sebagai fakta yang sudah
diketahui oleh banyak orang ini, setiap hari semakin meningkat. Bahkan dalam
investigasi majalah Fajar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Instika 2016, dilakukan
degan cara memaksa dan cara-cara yang tidak manusiawi lainnya.
Visit Sumenep dan penjarahan tanah dibeberapa
wilayah Kabupaten Sumenep, menjadi salah satu perwujudan riil kapitalisme yang
telah merebut alat produksi warga untuk kepentingan modal industri perusahaan atau
individu. Upaya ini telah dilakukan, melibatkan berbagai elemen mulai dari
pemerintah atau masyarakat lokal untuk menjadi “kaki tangan” dalam mendekati
warga agar mau melepas tanahnya untuk dikuasai. Konspirasi birokrasi dan pengusaha
dalam proyek kapitalisme ini, jelas mendudukkan masyarakat desa yang notabene
santri, sebagai individu yang akan menjadi kuli di tanahnya sendiri.
Seiring berjalannya
waktu, sampai cap halal pun untuk wisata di Sumenep dilakukan. Sebagaimana yang
dikatakan oleh orang nomor satu di Sumenep ini, A. Busyro Karim. “Tidak perlu khawatir, sebab semuanya sudah serba sehat
dan halal. Nantinya pihak travel yang akan memanjakan para wisatawan,
berhentinya dimana, makannya dimana, sholatnya dimana, maka semuanya insya
Allah akan terjaga.” Kendati
jaminan untuk para wisatawan sudah ditanggung, namun tetap tidak ada tanggungan
khusus untuk para rakyat pribumi.
Keadaan
semacam inilah, agama direduksi sebagai prangkat simbolik untuk mengafirmasi
seluruh praktik kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok dominan, yang
terus berusaha dengan berbagai cara memperkuat dominasi kemapanannya sendiri.
Pada fase ini, agama dibuat berdiri di tengah lingkaran permainan kaapitalisme
itu sendiri. Usaha melakukan Islamisasi pada kapitalisme ini, semakin menonjol
saat seperti rencana Visit Sumenep telah lebih dulu di cap halal. Usaha
menghalalkan Visit Sumenep (kapitalisme) dimungkinkan sejuh dilatekkan sebagai
rangkaian praktik secara vertikal, dengan melenyapkan implikasi sosiologis
dalam diri agama itu sendiri.
Dalam fenomana ironis ini, Islam
ploretar hadir, sebagai peghayatam Islam Santri-Marxisme untuk membangun kembali kesadaran empatik
terhadap kaum mustadh’afîn. Yang
lahir berdasarkan fenomena pertentangan kelas, antara kelas penindas (mala’ atau mutraf) dan kelas tertindas (mustadh’afîn).
Termasuk pula, antara para petani atau buruh dan elit-politik serta pemilik
modal. Kesadaran impatik dalam bingkai Islam ploretar, bedasarkan
kerangka materialistik, yang mengafirmasi seluruh ide-ide tentang keIslaman,
termasuk dalam aspek teologi, syari’ah dan tasawuf, nicaya bersifat material:
di mana agama harus bertolak dari fenomena eksternal-sosial-empirik.
Materialisme, sebagai suatu ontologi
sosial (baca: pemikiran mendasar tentang masyarakat, individu, dan sejarah),
dalam hal ini, sebagai suatu bentuk kesatuan otonom dari relung-doktrin agama itu
sendiri. Semacam spirit “teologi pembebasan”-nya
Asghar Ali Engineer, “Islam kiri”-nya Hassan Hanafi, dan “post-tradisionalismenya”-nya
Muhammad Abed al-Jabiri (diterjemahkan oleh Ahmad Baso), namun lebih radikal
dari sekedar transformasi aqidah pada ranah sosial-material seperti yang mereka
lakukan. Karena pada posisi ini, Islam proletar lebih menonjolkan diri bertolak
dari kontradiksi kelas. Di sisnilah perwujudan Islam melalui pendekatan
materialisme historis mendapatkan posisinya yang sangat vital.
Mendudukkan Islam dalam “materialisme historis”-nya Marxis berarti kita juga melakukan reorientasi
keagamaan.
Bagaimana kemudia seluruh prangkat doktrik keagamaan itu sendiri dapat lebih
akrab dan pula kritis terhadap realitas yang penuh dengan selubung jebakan
berbahaya. Sehingga pada fase ini agama (baca: Islam) para
santri, tidak lagi dihayati sekedar jalan menuju surga, tapi dalam aspek yang
lain, juga harus dipahami sebagai “agama perlawanan”. Perlawanan terhadap
seluruh elemen yang senantiasa menggunakan agama sekedar sebagai kendaraan untuk
mencapai keinginan pribadinya. Kelompok yang selalu mendudukkan agama sebagai
panggung pencitraan ini, adalah aktivitas yang gemar dilakukan oleh para elit
politik dan pengusaha di Sumenep.
Maka
dari itu, Islam proletar menjadi argumentasi alternatif untuk meletakkan agama
tidak sekedar foumulasi aqidah, melainkan juga kritik sosial untuk melihat
praktik-praktik diskriminatif sebagai problem yang harus diselesaikan sebagai
bagian garis perjuangan agama di Madura, utamanya Sumenep. Posisi strategis
santri dalam stuktur sosial masyarakat Madura butuh kembali mengkonsolidasikan
diri atas nama kedaulatan bersama. Maka dari itu, Islam Proletar mencoba
mendefinisikan diri sebagai Islam yang memiliki spirit permbebasan dan strategi
gerakan yang digali dari tiga dimensi sekaligus, kearifan lokal, Marxisme dan
nilai-nilai sosial Islam rahmatan lil ‘alamin.
Tiga
dimensi di atas ini menjadi trilogi pokoh dalam menerjemahkan Islam Proletar di
Madura. Sehingga, dalam praktiknya, pada waktu tertentu, ia bisa saja menjadi
kritik sosial, lalu dapat pula berubah menjadi strategi gerakan recolusioner,
dengan tetap memegang teguh kearifan lokal Madura sebagai fenomena objektif
atas bersatunya spktrum ajaran Islam dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Dan
pada akhirnya penghayatan Santi-Marxisme ini, sebagai eksperimentasi
metodologis, kembali mengaktualkan posisi vital santri dalam dinamika
sosio-keagamaan masyarakat Madura berhadapan dengan kapitalisme yang pelan tapi
pasti berusaha menjinakkan agama dalam pusaran politis yang rumit, sepihak dan
diskriminatif. Alhasil, Santri-Marxisme berakhir dengan seruan: bersatulah kaum
santri!